LPH: Penalaran Hukum (Aspek Ontologis, Epistimologis,dan Aksiologis)
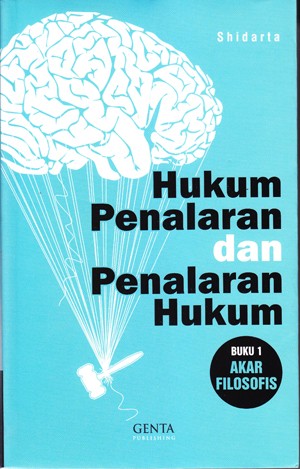
Apa kabar netijen semua? semoga baik-baik semua ya,
nah pada kesempatan kali ini saya mau nulis lagi di blog ini setelah sekian
lama absen nulis dikarenakan banyak kesibukan (sok sibuk). Kali ini saya akan
menulis tentang penalaran hukum (Aspek Ontologis, Epistimologis,dan Aksiologis)
untuk memenuhi tugas amata kuliah Logika dan Penalaran Hukum, namun dalam
mengerjakan tugas ini saya tidak merasa terpaksa (ada dikit) dan terbebani,
justru dengan adanya tugas ini lebih memacu saya untuk menulis lagi dan berbagi
pengetahuan sama netijen semua. Saya mengambil referensi dari buku yang
berjudul Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum yang ditulis oleh Prof. B.Arief
Sidharta, SH., MH. Kalau dalam penulisan ini saya ada kekurangan atau
ketidakjelasan mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar, apabila netijen
sekalian punya pedapat lain saya persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya di
kolom komentar sekalian bisa nambah pengetahuan. Nah langsung aja nih tanpa basa
basi lagi langsung aja dimulai.
Aspek Ontologis, Epistimologis,dan Aksiologis
1. Aspek Ontologis
Aspek
ontologis antara lain mempersoalkan apa yang merupakan hakikat dari sebuah
realitas, dari sini muncullah berbagai pendekatan diantaranya ada yang melihat
suatu realitas sebagai sebuah materi, ada juga yang melihat realitas berupa
ide. Dari dua pendekatan ini muncul beberapa pandangan, yaitu pandangan
monoistis dan dualisme, pandangan monoistis menganggap bahwa dari dua
pendekatan yang tersdia diatas hanya memilih salah satu saja (alternatif),
sebaliknya pandangan dualistik menganggap bahwa hakikat realitas harus
menggunakan kedua pendekatan tersebut.
Materialisme menganggap bahwa hakikat dari
segala sesuatu yang ada itu adalah
materi.Tidak mungkin suatu yang tidak ada (non materi) dapat menghadirkan
sesuatu yang materi. Seperti diumpamakan hakikat manusia yang terdiri dari roh
dan badan apabila roh/jiwa hanya berdiri sendiri tanpa ada benda materi (dalam
hal ini badan manusia) maka menjadi tidak berarti. Dalam perkembangannya materialisme
telah berkembang menjadi beberapa versi pemikiran seperti
materialisme-rasionalistis, materialisme parsial, materialisme-antropologis,
materialisme-dialektis, atau materialisme-historis.
Kemudian ada pandangan yang kedua yaitu
Idealisme yang merupakan kebalikan dari materialisme. Menurut idealisme ide
lebih hakiki jika dibandingkan dengan materi karena ide merupakan “pengada”.
Ada banyak pembedaan idealisme, menurut Nicholas Rescher ia membaginya menjadi
dua kelompok yaitu kelompok pertama adalah causal
idealism kelompok ini memandang bahwa segala sesuau itu lahir dari
aktivitas mental yang sesuai dengan hukum kausalitas (sebab akibat), kelompok
yang kedua yaitu supervenience idealism mereka
juga berpendapat segala sesuau itu lahir dari aktivitas mental, hanya saja
mereka tunduk kepada ketergantungan eksistensial. Plato menjelaskan aliran
berpikir idealisme, ia menyebutakan bahwa materi itu bisa saja hilang, namun
ide tentang materi tersbut tidak akan hilang. Misalnya, seekor kuda ia dapat
berbeda-beda warna,berat, dan penampakannya atau menjadi muda, tua, sehat,
sakit, dan mati. Jadi apabial kuda itu mati atau musnah maka materi dari kuda
itu “hilang” namun sebaliknya ide tentang kuda itu akan terus ada (abadi)
kendati materi dari si kuda itu telah musnah.
Semua wujud realitas di seluruh alam semesta
dapat dijadikan sebagai objek/contoh, namun pada kesempatan ini yang menjadi
objeknya adalah realitas hukum. Polemik seputar aspek ontologis dapat dirumuskan
dengan saderhana yaitu apakah hukum iu termasuk ke dalam materi, atau ide (monoistis)
atau bahkan hukum itu dapat dimasukkan keduanya sekaligus? Cicero seorang filsuf
romawi memberikan tanggapan akan rumusan tersebut ia berpendapat bahwa hukum
itu menyatu dengan masyarakat, namun dilain sisi hukum juga merupakan akal budi
setiap manusia. Hal tersebut menunjukkan keterkaitan anatara konsep hukum
dengan kebudayaan manusia. Hukum bukan hanya produk politik melainkan hukum itu
juga produk kebudayaan manusia.
Kemudian Clifford Geertz memberikan
pandangan kebuadayaan manusia dan kaitannya dengan hukum, ia membaginya ke
dalam beberapa wujud (bentuk), yaitu:
1. Wujud
kebudayaan yang pertama bersifat abstrak, yang berupa aturan mengenai tata
kelakuan seorang manusia, serta mengendalikan dan memberi arahan atas perbuatan
tersebut. Contoh dari wujud yang pertama ini adalah norma, perundang-undangan,
asas keadilan, dan kebenaran.
2. Wujud
kebudayaan yang kedua ialah sistem sosial yang terdiri dari aktivitas interaksi
manusia, semua bentuk interaksi ini membentuk pola tertentu berdasarkan tata
kelakuan (wujud kebudayaan yang pertama). Pada wujud kebudayaan ini sudah lebih
konkret karena sudah bisa diamati secara langsung .
3. Wujud
kebudayaan yang ketiga, ialah semua benda yang bersifat fisik seperti artefak,
candi, smapai ke chip komputer.
2. Aspek Epistimologis
Manusia
dapat mengembangkan pengetahuaannya karena mereka memilik dua modal, yaitu bahasa
yang komunikatif dan kemampuan berpikir, dengan dua modal tersebut manusia dapat
melakukan kegiatan berpikir untuk menemukan pengetahuan yang benar.
Proses kegiatan berpikir ini disebut dengan penalaran. Penalaran dimaknai oleh
Lorens Bagus dalam tiga pengertian:
a. Proses menarik kesimpulan dari
pernyataan-pernyataan.
b. Penerapan logika dan atau pola pemikiran abstrak
dalam memecahkan masalah atau tindakan perencanaan.
c. Kemampuan untuk mengetahui beberapa hal tanpa bantuan
langsung persepsi indrawi atau pengalaman langsung.
Ia menambahkan bahwa penalaran itu mempengaruhi
dan membentuk setiap kegiatan sadar. Secara sederhana suatu proses penalaran
dalam penelitian ini lebih diartikan sebagai proses atau kegiatan berpikir
menurut pengertian pertama dan kedua yang telah disampaikan oleh Lorens Bagus.
Penalaran hanya terbatas pada kegiatan yang rasional, hal ini disebabkan karena
penalaran memang memiliki keterkaitan dengan logika. Sehingga logika perliu
dibantu oleh disiplin lain yaiut bahasa, bahasa diperlukan karena objek yang
digunakan. Dengan demikian suatu penalaran yang mengandalkan rasionalitas harus berkolaborasi dengna modalits seperti
intusis, dan empiris. Sayangnya kolaborasi tersebut tidak sepenuhnya terjadi paling tidak dalam
wacana filsafat penngetahuan (epistimologi) ,sehingga terjadi dikotomi antara aliran empirisme dengan rasionalisme.
Empirisme berasal dari kata empirik yang
berarti pengalaman, empirisme adalah aliran dasar dalam epistimologi yang
menganggap sumber satu-satunya pengetahuan bagi manusia adalah pengalaman,
tepatnya melalui observasi indrawi. Sebab, pancaindra manusia tidak mungkin
melakukan kebohongan sehingga apabila terjadi kesalaan itu disebabkan kareana kesalahan interpretasi manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh teori tabula rasa, yang mana pada dasarnya manusia lahir tidak membawa pengetahuan apa-apa pengalaman hiduplah yang mengajarkan manusia segala seusatu sehingga manusia itu dapat menghimpun pengetahuan yang telah ia dapatkan. Dengan kata lain seorang manusia menjadi tahu berkat pengalaman yang telah ia dapatkan.
Kemudian muncul aliran lain yaitu rasionalisme yang berkebalikan dari empirisme, aliran ini menganggap sumber pengetahuan satu-satunya adalah akal budi manusia, kendati demikian rasionalisme tidak menolak peran indrawi (seperti yang digunakan di aliran empirisme) dalam proses pencarian manusia akan pengetahuan, namun peran indrawi di aliran ini hanya sebagai perangsang kerja akal. Hal ini dibuktikan dengan ketidakpercayaan akal secara otomatis terhadap pengetahuaan yang diperoleh secara indrawi, akal akan bekerja untuk menguji pengetahuan yang didapat oleh indra apakah pengetahuan tersebut masuk akal atau tidak. Dengan demikian menurut kaum rasionalis jelas akal berada diatas pengalaman indrawi.
Untuk mengurangi pembenturan diantara dua aliran di atas, Imanuel kant berpendapat bahwa tidak perlu untuk mempertentangkan kedua aliran tersebut karena keduanya dapat saling mengisi. Maka dari itu, kant membangun filsafat kritis yang berpedoman bahwa "pemikiran tanpa isi adalah kosong, sedangkan intuisi tanpa konsep-konsep adalah buta". Isi dari intuisi disini menyangkut data empiris, sementara konsep adalah bentuk pikiran.
3. Aspek Aksiologis
Kiranya sudah mejadi aksiomabahwa tindakan manusia adalah fungsi dari kepentingannya. Pemenuhan kepentingan inilah yang menjadi tujuan dari tindakannya, bahkan dalam seluruh kehidupan seseorang. Jika suatu tindakan dilatarbelakangig oleh kehendak (motivasi), maka tentu saja menjadi pertanyaan besar tentang ada tidaknya kebebasan kehendak manusia dalam bertindak.
Aliran yang disebut "Religious Absolutism" termasuk kelompok manusia yang tidak punya kehendak bebas. Menurut aliran ini manusia dibatasi oleh kekuatan yang berasal dari luar jiwa manusia (Tuhan). Dalam sejarah Islam ada kelompok yang menganggap bahwa keseluruhan tindakan manusi adalah manifestasi dari tindakan Tuhan. Tuhan telah menetapkan dan manusia hanya menjalankan sesuai apa yang telah digariskan oleh Tuhan (absolut), kalau diibaratkan manusia itu seperti mobil yang dikendalikan oleh remote control jadi segala kehendak manusia itu telah diatur oleh takdir Tuhan. Kelompok ini dinamakan Jabariyah.
Kemudian pandangan aliran diatas dibantah oleh tentang intersepenndensi manusia. Dalam sejarah Islam ada kelompok yang bernama Qadariyah mereka tidak secara total menolak adanya pengendalian Tuhan dalam kehendak manusia, namun pengendalian itu hanya sebatas pada penciptaan, memeliara, menggerakkan, atau mengembsngkan segenap ciptaannya menurut hukum yang tertib dan tetap.
Ada banyak aliran pemikiran yang menelaah aspek aksiologis dari tindakan manusia, yaitu:
Nah sekian dulu nih tulisan untuk kali ini semoga apa yang telah disampaikan di atas dapat berguna bagi netijen semua, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan namanya juga manusia tempatnya salah dan dosa, sampai jumpa di tulisan berikutnya ya3. Aspek Aksiologis
Kiranya sudah mejadi aksiomabahwa tindakan manusia adalah fungsi dari kepentingannya. Pemenuhan kepentingan inilah yang menjadi tujuan dari tindakannya, bahkan dalam seluruh kehidupan seseorang. Jika suatu tindakan dilatarbelakangig oleh kehendak (motivasi), maka tentu saja menjadi pertanyaan besar tentang ada tidaknya kebebasan kehendak manusia dalam bertindak.
Aliran yang disebut "Religious Absolutism" termasuk kelompok manusia yang tidak punya kehendak bebas. Menurut aliran ini manusia dibatasi oleh kekuatan yang berasal dari luar jiwa manusia (Tuhan). Dalam sejarah Islam ada kelompok yang menganggap bahwa keseluruhan tindakan manusi adalah manifestasi dari tindakan Tuhan. Tuhan telah menetapkan dan manusia hanya menjalankan sesuai apa yang telah digariskan oleh Tuhan (absolut), kalau diibaratkan manusia itu seperti mobil yang dikendalikan oleh remote control jadi segala kehendak manusia itu telah diatur oleh takdir Tuhan. Kelompok ini dinamakan Jabariyah.
Kemudian pandangan aliran diatas dibantah oleh tentang intersepenndensi manusia. Dalam sejarah Islam ada kelompok yang bernama Qadariyah mereka tidak secara total menolak adanya pengendalian Tuhan dalam kehendak manusia, namun pengendalian itu hanya sebatas pada penciptaan, memeliara, menggerakkan, atau mengembsngkan segenap ciptaannya menurut hukum yang tertib dan tetap.
Ada banyak aliran pemikiran yang menelaah aspek aksiologis dari tindakan manusia, yaitu:
- Idealisme etis adalah aspek aksiologis yang meyakini bahwa baik buruknya suatu tindakan telah ditetapkan oleh nilai-nilai spiritual.
- Deontologisme-etis, kata deontologi diambil dari kata deon (bahasa Yunani) yang artinya apa yang harus dilakukan (kewajiban). Deontologisme dalam hal ini menilai baik buruk suatu tindakan dari tindakan tersebut sendiri (missal, melihat pada hukum positif), bukan melihat pada aspek akibat dari tindakan tersebut.
-
Teleologisme-etis atau yang disebut juga sebagai eudemonisme, adalah pandangan aspek aksiologis yang mengukur baik-buruk sesuatu dari hasilnya. Eudemonisme ini melihat bahwa segala tindakan manusia pasti meiliki tujuan tertentu, baik untuk diri sendiri (egoism), maupun untuk masyarakat di sekitarnya (utilitarianisme).
Wassalamualikum wr wb
................................................................................................................
Daftar Pustaka
Arief Sidharta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

Komentar
Posting Komentar